Testimoni Penyintas HIV di Pontianak, Antara Cinta dan Ironi

Pontianak, IDN Times - Kisah itu bermula di tahun 2017, kisah yang kukira bisa mengubah kehidupanku dengan keterpurukan. Tapi, seluruh orang tiba-tiba memberiku hujatan, menjauhiku, memberiku stigma serta omongan yang tak enak di hati.
Aku adalah seorang ibu rumah tangga (IRT) menikah dengan seorang pria yang ternyata mengidap virus HIV (human immunodeficiency virus), orang-orang menyebut itu adalah virus mengerikan.
Saat itu aku tak tahu tentang virus HIV, aku menikahi suamiku atas dasar kasih sayang. Aku juga tak menaruh curiga apa pun dengannya, pernikahan itu berlangsung di tahun 2015. Aku dan suamiku hidup layaknya pasutri (pasangan suami istri) pada umumnya.
1. Tahun 2017 suamiku meninggal dunia, virus itu menyebar ke dalam tubuhku

Kehidupan berjalan seperti biasa, namun tiba-tiba saja di pertengahan tahun 2017 suamiku jatuh sakit, badannya mulai melemah tak karuan. Aku ingat betul saat itu tanggal 12 April 2017, sejumlah tenaga kesehatan datang ke rumahku.
Mereka memeriksa darahku, juga darah suamiku. Aku sendiri tak mengetahui pengambilan sampel darah itu untuk apa. Tapi belakangan aku baru sadar bahwa yang memanggil sejumlah tenaga kesehatan itu dari keluargaku sendiri.
“Sampel darah ini untuk apa bu?” tanya ku kepada salah satu nakes.
Namun mereka tak kunjung memberitahukanku untuk apa darah yang mereka ambil itu. Mereka cuman bilang kalau ini adalah pengambilan darah biasa saja.
Saat itu aku tak curiga dan merasa biasa saja. Keesokan harinya, aku diminta untuk datang ke puskesmas untuk dites ulang, katanya agar pemeriksaan lebih akurat. Aku hanya menuruti mereka karena aku menganggap ini juga demi kesehatanku.
Aku pergi ke puskesmas ditemani dengan salah satu keluargaku, sampai di sana ternyata aku disuruh untuk mengeluarkan dahak, mereka bilang kalau dari sampel dahak yang aku berikan aman-aman saja.
Pengambilan darah kedua, kali ini cukup membuatku deg-deg an. Usai pengambilan darah, aku disuruh untuk menunggu sekitar 30 menit, setelahnya aku langsung disuruh pulang tanpa diberitahukan hasil pemeriksaan darah itu.
Bahkan saat di perjalanan pulang pun, keluargaku tak ada yang memberitahukanku hasil dari pemeriksaan darah itu.
Malam harinya, suamiku yang sudah sakit mulai melemah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Aku membawanya ke RSUD Soedarso, salah satu rumah sakit pemerintah di kotaku.
Sampai di sana, suamiku dibawa ke IGD dan ditangani oleh para tenaga kesehatan. Kurang lebih 3 jam aku menunggu, aku terus gelisah dan cemas melihat keadaan suamiku yang semakin melemah.
Jantungku berdetak sangat kencang ketika dokter mengatakan bahwa suamiku tertular virus HIV AIDS dan sudah menjalar ke bagian kepala.
Aku kaget bukan kepayang, seperti dunia akan lengap, bukan karena aku takut tertular tapi aku lebih mencemaskan kondisi suamiku yang sedang terbaring di IGD rumah sakit dengan penyakit itu.
Baru kuketahui ternyata suamiku pernah menjadi lelaki seks lelaki (LSL) sebelum dia menikah denganku. Waktu itu aku memang tak tahu apa itu LSL, dua tahun menikah dengannya aku merawat dan menjaga kondisi kesehatan suamiku, begitulah yang terjadi.
Suamiku telah 3 hari dirawat di rumah sakit, aku dipanggil perawat, mereka memberikanku konseling dan menyarankanku untuk memeriksakan kesehatanku di fasilitas kesehatan lain.
Dalam 3 hari itu, hanya aku dan ayahku yang mengetahui suamiku ternyata mengidap HIV. Namun hari yang menakutkan itu tiba, hari yang ingin kuhapus dalam kalender, tanggal 16 April 2017 suamiku meninggal dunia.
Saat sekujur tubuh ini mulai melemas, aku baru diberi selembar kertas tanpa amplop, tinta dalam selembar kertas itu menyebutkan bahwa aku juga reaktif HIV.
2. Stigma dimulai dari jenazah suamiku dibawa pulang ke rumah

Tak perlu waktu lama, kabar aku menghidap HIV ini pun tersebar ke keluarga, bahkan tetangga sekitar. Saat itu, kehidupanku dipenuhi dengan stigma-stigma dan diskriminasi dari mereka.
Diskriminasi dimulai saat jenazah suamiku dibawa pulang kerumah. Tetangga hingga sanak saudara ketakutan untuk memandikan jenazah suamiku. Keluarga yang aku rasa mereka adalah orang terdekatku pun menghindar sekadar untuk memandikan almarhum.
Bahkan mereka menyarankan kepada orang-orang yang memandikan jasad suamiku harus memakai jas hujan, padahal aku sudah membantah dan meminta mereka untuk memandikan jenazah suamiku layaknya jenazah pada umumnya.
Perlakuan ini menurutku sungguh menyayat hati.
Tanggal 18 April 2017, aku melakukan pengobatan di Rumah Sakit Jiwa Pontianak yang saat ini sudah berubah menjadi Klinik Utama Sungai Bangkong. Di sana aku melakukan terapi ARV, terapi yang biasa dilakukan oleh penyintas HIV.
Aku ingat betul saat itu tanggal 19 April 2017, dokter memberikanku obat ARV. Obat-obatan ini diberikan selama dua minggu penuh. Efek obat-obatan ini menciptakan halusinasi yang cukup tinggi, kepalaku sungguh sakit.
Baru 7 hari melakukan terapi, aku terus-terusan mendapat stigma yang tak lain adalah dari orang terdekatku sendiri. Beberapa anggota keluarga yang tinggal satu atap denganku memisahkan perabotan makan dan minum khusus untukku.
Aku diasingkan, kamar tidurku dibongkar, aku dibuatkan tempat tidur yang tentunya jauh dari mereka. Aku disarankan untuk tidur dengan satu alas kasur saja, mereka takut aku menularkan virus ini.
Ada kejadian pilu yang aku alami saat masih mengalami efek samping terapi obat. Saat itu aku terjatuh dari anak tangga di rumah, badanku mulai lemah tak ada satupun anggota keluarga yang menolongku.
Ada darah yang keluar dari tubuhku, 30 menit aku meminta pertolongan, tak ada satupun dari mereka yang membantu, dengan badan yang lemas aku mencoba untuk membersihkan darahku sendiri. Aku sedih dan terpuruk.
Terapi hari ke-12 berlangsung, efeknya membuat sekujur badanku terkelupas merah dan bengkak. Hari ke-14 aku disarankan untuk berhenti terapi obat dalam dua minggu, mungkin saja dokter beranggapan, aku kurang cocok dengan jenis obat itu.
Setelah berhenti sementara, aku melanjutkan terapi obat dengan jenis ARV yang berbeda, badanku terasa lebih nyaman dari sebelumnya walaupun efek samping itu masih terasa.
3. Aku memutuskan untuk pulang ke kampung

Aku tak tahu sampai kapan terapi ARV ini dilakukan, tapi yang pasti sampai saat ini aku masih saja mendapatkan stigma dari keluarga. Aku yang hancur dan kondisi tubuh yang lemah ini tak mendapat dukungan dari keluarga sedikitpun.
Karena tak bekerja, aku tak memiliki uang untuk bertahan hidup. Untuk membeli makanan saja susah, tapi aku bersyukur sampai hari ini niatan untuk bunuh diri sedikitpun tak ada terlintas dalam benakku.
Setelah 3 bulan pengobatan berjalan, ayahku di kampung menyarankan aku untuk pulang. Dia tak tega melihat putrinya hidup sendirian dengan penyakit yang diidapnya.
Sampai di Pulau Jawa, di luar dugaan. Aku didukung penuh oleh keluargaku yang ada di sana, jika dipikir-pikir aku sudah 11 tahun tak pernah pulang ke kampung halaman, walaupun begitu, mereka tetap menerima dan memelukku ketika sampai di rumah.
Sehari-hari aku diberikan semangat untuk bangkit, motivasi-motivasi yang diberikan membuatku merasa hidup bagaikan orang normal yang hidup sehat tanpa bayang-bayang HIV.
Tiga bulan belakangan aku bangkit, semua berkat semangat dan dukungan dari keluargaku di Jawa. Aku bisa berfikir jernih bahwa aku bisa melakukan apa pun tanpa batasan, hingga akhirnya aku berani untuk pulang kembali ke Pontianak.
4. Dia adalah pria yang menerima statusku sebagai penyintas HIV
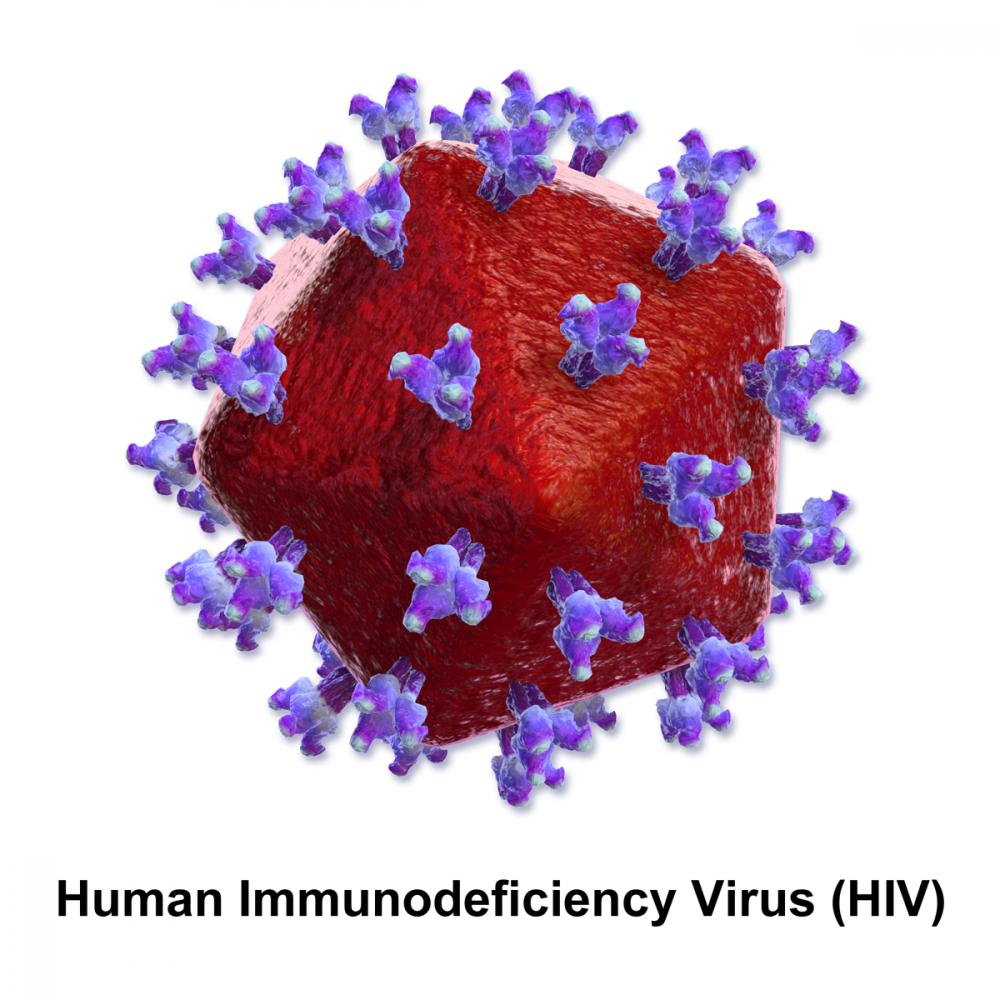
Usai bangkit dari keterpurukan, aku kembali membuka hati. Di usiaku yang terbilang masih cukup muda, aku mencoba membuka hati. Mereka datang dan pergi, silih berganti. Sejak kepulanganku ke Pontianak, aku juga bekerja sebagai pendukung sebaya ODHA (Orang dengan HIV/AIDS).
Saat itu, aku ditolak oleh 3 pria karena statusku. Mereka punya ribuan alasan untuk menolakku, aku tak banyak berkutik. Tapi tentu saja aku tak menyerah, tiba waktunya ada seorang pria yang datang kepadaku dan mau menerima kondisiku.
Aku ingat saat itu tahun 2020, dia adalah pria yang bisa menerima status sebagai penyintas HIV, padahal dia adalah pria yang sehat tanpa kurang apapun, tanpa virus apapun.
Kami melangsungkan pernikahan dan segera melakukan program hamil. Kami bolak-balik pergi ke dokter untuk konsultasi. Aku juga rutin mengecek viral load yang ada di dalam tubuhku, hasilnya selalu tidak terdeteksi dan aman.
Dokter memperbolehkanku untuk mempunyai anak, betapa bahagianya aku saat itu. Dokter memberitahukanku untuk rutin terapi obat. Dokter bilang karena viral load ku tak terdeteksi, dia bilang aku sama seperti orang normal lainnya maka dokter mengizinkanku untuk hamil dan memiliki anak.
5. Aku akhirnya hamil dan melahirkan seorang anak

Tiba waktu yang ditunggu-tunggu, aku hamil dan melahirkan seorang anak. Tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap bayiku tentu saja beda, mereka dengan sigap langsung melalukan profilaksis selama 6 minggu, katanya hal ini untuk pencegahan penularan virus dari ibu ke anak yang baru lahir.
Ngomong-ngomong, saat pernikahan dengan mendiang suamiku, aku sempat hamil, waktu itu usianya masih 1 bulan. Namun bayi kecil yang malang itu harus menghadap sang Ilahi. Imunitas tubuhku saat itu sangat lemah karena sudah tertular HIV. Namun kehadirannya dalam waktu 1 bulan itu membuatku tak patah semangat untuk melanjutkan kehidupan.
Kini aku bahagia, aku menjadi seorang ibu, melahirkan anak yang sehat, dan dia bersih dari virus HIV.
Ada kisah yang belum kuceritakan, saat-saat aku mau melahirkan ternyata aku masih juga diberikan diskriminasi dari salah satu dokter kandungan di salah satu rumah sakit pemerintah.
Saat itu, salah satu dokter kandungan ini melarang dan tidak memperbolehkan perempuan penyintas HIV hamil, bahkan dilarang melahirkan di sana. Karena sebelumnya aku sudah mendapatkan edukasi dari dokter, aku tentu saja membantah.
“Dok, tidak ada perbedaan perempuan penyintas HIV dengan perempuan yang normal di luar sana,” ucapku dengan tegas kepada dokter itu.
Beberapa kali aku melakukan USG di rumah sakit itu, masih saja aku diberikan stigma negatif. Sampai akhirnya pihak rumah sakit menolakku untuk melahirkan di sana dengan alasan dokter tersebut akan cuti, akhirnya aku memutuskan untuk lahiran di rumah sakit pemerintah lainnya.
Setelah 7 minggu anakku diberikan antibiotik profilaksis, alhamdulillah bayiku dinyatakan sehat dan tidak tertular HIV.
Aku harap dengan kisah hidupku yang cukup panjang dan penuh rintangan ini dapat membuka mata semua pembaca agar tak mendiskriminasi dan memberikan stigma negarif kepada penyintas HIV.
Aku juga berharap untuk para penyintas yang membaca kisahku ini, kalian itu hebat. Jangan pernah putus asa, kalau bukan kita sendiri siapa lagi yang akan melawan virus yang ada di tubuh ini. Jangan pernah menyerah walaupun kita sering diberikan stigma negatif. Cintailah diri kita sendiri, dan tetaplah hidup.
“Jangan pernah mengotak-ngotakkan penyintas, kita tidak ada bedanya,” pesanku.
6. Dinkes merilis 5.259 kasus HIV di Kalimantan Barat

Kasus HIV (human immunodeficiency virus) di Kalimantan Barat (Kalbar) sejak tahun 2003 sampai penghujung tahun 2023 secara keseluruhan mencapai 5.259 kasus yang dilaporkan.
Sebanyak 700 orang meninggal dunia, dan yang masih bertahan berjumlah 4.559 orang. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar Erna Yulianti mengatakan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA) didominasi oleh mereka yang berusia 20 sampai 60 tahun yakni 35,5 persen.
“Adapun secara keseluruhan kriteria penyintas untuk remaja dari usia 13 sampai 18 tahun ada 3,6 persen, ibu rumah tangga 2,4 persen. Namun usia 20 sampai 69 tahun itu termasuk populasi umum ada sebanyak 34,5 persen, sedangkan untuk lelaki seks lelaki (LSL) itu sekitar 24,1 persen,“ ungkap Erna, Jumat (8/12/2023).
Erna mengungkapkan, pihaknya melakukan pengobatan terhadap 3.586 penyintas atau sekitar 80 persen. 1.000 penyintas lainnya tak mau melanjutkan pengobatan tersebut.
“Tapi ini jadi pantauan kami agar 1.000 orang penyintas ini mau berobat karena hal tersebut berisiko terjadinya penularan,” tukasnya.