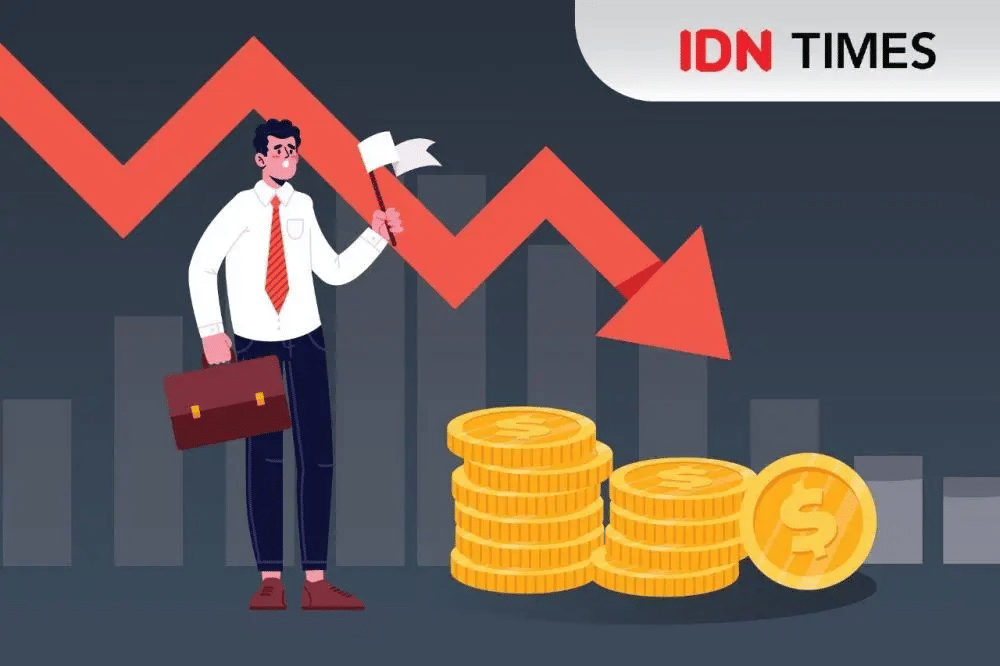BPS Klaim Kemiskinan Turun, Ekonom Unmul Sebut Itu Ilusi Data

Balikpapan, IDN Times – Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai penurunan angka kemiskinan di Indonesia dan Kalimantan Timur menuai kritik tajam dari kalangan akademisi. Ekonom Universitas Mulawarman, Samarinda, Purwadi Purwoharsojo, menilai bahwa indikator dan metodologi yang digunakan BPS dalam mengukur kemiskinan sudah tidak relevan dan jauh dari kondisi riil di lapangan.
Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin di Kaltim per Maret 2025 tercatat sebanyak 199,71 ribu jiwa, turun sekitar 12,2 ribu jiwa dibandingkan September 2024. Secara persentase, angka kemiskinan turun menjadi 5,17 persen dari sebelumnya 5,51 persen. Namun, Purwadi menilai klaim ini menyesatkan.
Adapun Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 8,47 persen, lebih rendah dari 8,57 persen pada September 2024. Jumlah penduduk miskin juga berkurang menjadi 23,85 juta orang.
“Indikator yang digunakan itu metode usang. Tidak sesuai dengan kenyataan sekarang,” kata Purwadi dihubungi dari Balikpapan, Selasa (29/7/2025).
1. Indikator lama, realitas baru

Purwadi menyoroti penggunaan indikator kemiskinan berdasarkan standar lama, yakni 1,9 dolar AS per hari atau setara sekitar Rp20-30 ribuan. Padahal, Bank Dunia sudah memperbarui standar garis kemiskinan menjadi 3,2 hingga 6 dolar per hari.
“Selisihnya itu bisa sampai empat kali lipat. Kalau pakai indikator Bank Dunia yang terbaru, angka kemiskinan kita bisa melonjak jadi 63 persen,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut perbedaan ini bukan hal sepele, karena menyangkut validitas data yang menjadi dasar berbagai kebijakan sosial dan ekonomi pemerintah.
2. Janji yang tak ditepati

Purwadi mengungkap bahwa BPS sebelumnya menjanjikan akan merilis indikator kemiskinan terbaru pada Juli 2025. Namun, janji tersebut tak ditepati. “Awalnya dijanjikan awal Juli, lalu pertengahan Juli, akhirnya keluar 25 Juli, tapi masih pakai indikator lama. Itu mengecewakan,” tegasnya.
Kondisi ini, menurutnya, membuat pemerintah terkesan tidak siap menghadapi kenyataan bahwa angka kemiskinan sebenarnya jauh lebih tinggi dari yang dirilis secara resmi.
Purwadi juga menyinggung klaim pemerintah yang menyebut Indonesia telah masuk kategori middle-income country, sebagaimana pernah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun, kebijakan pengukuran kemiskinan justru masih menggunakan standar rendah.
“Ngakunya kelas menengah, tapi masih pakai indikator zaman dulu. Ibaratnya ngaku makan keju, padahal yang dimakan cuma singkong. Ini tidak jujur,” kritiknya.
Purwadi menilai pemerintah terkesan enggan membuka data sesungguhnya karena bisa memicu keresahan publik. Ia juga mempertanyakan motif di balik sikap BPS yang tetap mempertahankan indikator lama.
“Jangan-jangan BPS tidak jujur dan malah jadi alat politik. Kalau indikatornya rendah, seolah-olah kemiskinan turun dan program berhasil, padahal kenyataannya jauh dari itu,” ucapnya.
3. Kebijakan bisa salah sasaran

Menurut Purwadi, penggunaan data yang tak akurat akan menyebabkan kebijakan pengentasan kemiskinan menjadi tidak tepat sasaran. Bantuan sosial, insentif, hingga subsidi bisa saja hanya menyasar sebagian kecil penduduk miskin.
“Misalnya harusnya ada 100 orang miskin, tapi karena indikator lama hanya terdata 25, berarti 75 orang lainnya tak tersentuh bantuan. Ini bahaya,” tegasnya.
Purwadi menyebut ketimpangan harga di berbagai daerah juga seharusnya diperhitungkan dalam penyusunan indikator kemiskinan. Misalnya, Rp20 ribu di Jakarta atau Balikpapan tak akan cukup untuk makan layak sehari, apalagi di daerah terpencil seperti Mahakam Ulu.
4. Gugat BPS soal indikator kemiskinan

Purwadi juga mendesak agar BPS dievaluasi dan bahkan digugat secara akademik agar lebih transparan dan jujur dalam menetapkan indikator.
“BPS harus turun ke lapangan, bukan bikin data lewat Google Maps. Harus sadar bahwa Rp20 ribu di Jakarta cuma cukup buat setengah porsi warteg,” tuturnya dengan nada menyindir.
Ia berharap pemerintah tidak lagi menutup-nutupi kondisi kemiskinan yang sebenarnya, karena data yang akurat adalah kunci kebijakan yang efektif.
“Kita ini ibarat sakit jantung stadium tujuh, tapi dikasih paracetamol. Gimana bisa sembuh?” pungkasnya.